Realita hidup ateis di negeri agamais
Penulis: Ninik Yuniati
Editor:

KBR, Jakarta - Peter -bukan nama sebenarnya- harus menjelaskan panjang lebar saban ditanya mengapa memilih menjadi ateis. Kata-kata yang dilontarkan pun dipilih seksama, agar tak disalahpahami.
“Kalau ada orang nanya, ‘Tuhan itu ada apa ga?’ Ateis akan bilang ‘aku nggak percaya’. Kalau agnostik akan bilang, ’aku enggak tahu’. Itu perbedaan antara ateis dengan agnostik. Sehari-hari, aku hidup secara ateistik, tapi kalau label, aku lebih nyaman dengan agnostik,” kata pria 40 tahun ini.
Lewat pemaparan mendalam, Peter ingin menekankan bahwa ia menempuh perjalanan panjang untuk sampai pada keputusan menjadi ateis.
“Sekalipun (ateis) itu istilahnya menakutkan sebenarnya, terutama bagi orang yang sepanjang hidupnya, sampai dengan saat itu, beragama, percaya dengan Tuhan dan tahu bahwa istilah itu punya sejarah, punya konotasi yang sangat negatif di Indonesia,” imbuhnya.
Peter lupa kapan tepatnya momen itu terjadi. Yang jelas sudah lebih dari 10 tahun ia tak lagi mempercayai keberadaan Tuhan.
Peter terlahir dari keluarga Kristen yang cukup taat. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Kristen sampai SMA.
Menginjak usia remaja, satu demi satu pertanyaan mulai mengusik benak Peter. Banyak ajaran yang menurutnya tak masuk akal.
“Ada pendeta yang berkhotbah, kalau orang sakit, itu karena dia berdosa, kalau orang miskin itu karena kurang iman. Aku melihat, dari sekelilingku. Kayaknya itu nggak benar deh. Sakit itu, karena penyakit menular, atau bisa genetik, kondisi lingkungan, atau gaya hidup buruk. Itu lebih masuk akal daripada sesederhana sakit itu karena dosa,” jelas Peter.
Baca juga:
Potret Media Alternatif di Tengah Ancaman KUHP Baru (Bagian 1)
Potret Media Alternatif di Tengah Ancaman KUHP Baru (Bagian 2)

Masyarakat sipil gencar mengkritik RKUHP karena masih memuat pasal-pasal problematik yang rentan menjerat kelompok rentan.(Foto: ANTARA/Rivan)
Di bangku kuliah, Peter berkenalan dengan beragam orang dan pengetahuan. Keyakinannya terhadap agama makin redup, ia pun berhenti ke gereja.
“Sampai satu titik merasa bahwa apa yang ditawarkan oleh agama, itu tidak lagi memadai untuk aku pakai sebagai pedoman hidup yang baik. Aku lebih baik mencarinya dari luar agama,” ungkap pekerja swasta yang berdomisili di Jabodetabek ini.
Peter mulai mengidentifikasi diri sebagai ateis usai membaca tulisan di sebuah media.
“Artikel mengenai ateis di Indonesia. Terus aku jadi merenungkan, kayaknya aku juga sama dengan orang yang diwawancarai itu. Jadi di situ titik di mana, kayaknya aku ateis juga deh,” tutur dia.
Baginya, menjadi ateis, bukanlah proses mudah, karena harus melepaskan sesuatu yang diyakini dan dihidupi sejak kecil.
“Karena sampai satu titik, yaitu merasa hilang, merasa enggak punya pegangan. Apa yang sebelumnya diberikan oleh agama, misalnya kayak pedoman moral atau ritual atau komunitas, pada akhirnya aku harus cari sendiri,” tambahnya.
Di sisi lain, jalan kompromi dengan tetap beragama juga enggan ditempuhnya, karena berlawanan dengan hati nurani.
“Karena memang enggak dari hati, gimana dong? Kayak disuruh mencintai sesuatu yang memang kita ga sukai. Harus menjalani itu seumur hidup. Sama kayak orang beragama deh. Agamanya A, disuruh mengaku bahwa dia agamanya B seumur hidup,” terang Peter.
Lambat laun, ia menemukan komunitas ateis di media sosial, tempatnya bertukar pikiran dengan leluasa.
“Lalu mulai bergaul dan merasa bahwa ‘oh dalam banyak hal kita cocok ya’, enggak dalam semua hal, karena di komunitas ateis-agnostik itu pun beragam pandangannya. Tapi sekurang-kurangnya dalam hal satu itu, kita sama dan bisa saling berkeluh kesah, bisa saling mendukung. Bisa berempati sih,” kisahnya.
Baca juga: Alexander Aan: Ada Diskriminasi, Terlalu Bodoh kalau Diam Saja
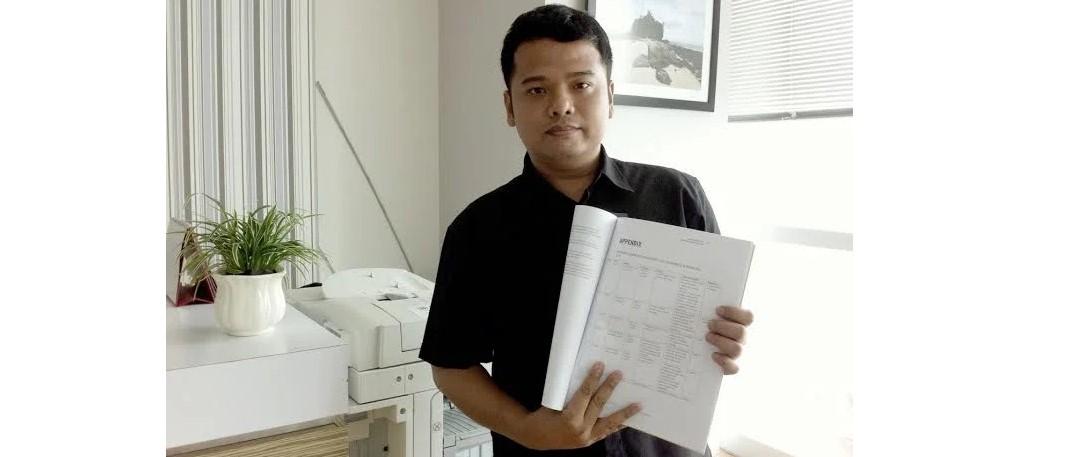
Alexander Aan, CPNS di Dharmasraya, Sumatera Barat dihukum 2,5 tahun penjara pada 2012 atas penistaan agama dengan menggunakan pasal 156a KUHP lama. Ia mengaku diri sebagai ateis. (Foto: KBR/Evelin).
Penerimaan keluarga
Peter pun berani berterus terang kepada keluarga dan mereka bisa menerima.
“Ini berbeda dari pengalaman banyak teman (ateis) lain. Mereka ada yang diusir, dibuang. Kebanyakan ya harus pakai 'topeng', karena enggak mau menanggung konsekuensinya. Ada yang ditolak dari pekerjaan, ada juga yang punya masalah di sekolah atau kuliah,” ungkap Peter.
Sadar bahwa ateis rentan didiskriminasi, Peter selektif dalam berteman.
“Aku enggak tahu orang yang aku ajak bicara akan bisa menerima apa enggak? Jadi, pilih-pilih kata yang mau dipakai dalam percakapan. Bukan berarti harus berbohong, tapi enggak perlu mengungkapkan, kalau enggak ada keperluannya juga,” ujar dia.
Peter menegaskan tidak anti dengan orang beragama. Diakuinya, tak sedikit orang yang mendapat manfaat dan menjadi lebih baik karena beragama.
"Justru aku paham kenapa orang beragama, karena aku pernah di posisi mereka. Aku menyadari ada manfaat dari agama, membuat orang punya ketenangan hati, tujuan hidup, pedoman moral," ucap Peter.
Penghormatan terhadap orang beragama, ditunjukkan dalam kesehariannya berelasi.
“Aku punya sahabat, dia beragama lumayan taat, tapi kita bisa saling mengasihi, saling mendukung. Saking biasanya jadi ga istimewa. Kayak ‘wah ini adalah keindahan toleransi’, ya enggak, ini adalah persahabatan antara dua orang. Jadi biasa aja. Tapi aku bukannya enggak mengapresiasi, aku sangat bersyukur dengan persahabatan itu,” kata Peter.
Peter berharap bisa mendapati banyak relasi semacam ini. Namun, asa itu ibarat masih jauh panggang dari api. Sebab, ateis belum mendapat tempat di negeri ini. Stigma dan diskriminasi masih lekat mengiringi.
“Sedih, Indonesia masih enggak bisa terima perbedaan. Masih menganggap bahwa, kita ini berbeda, oleh karena itu berbahaya. Padahal kita orang-orang biasa, lahir di Indonesia, sekolah sepanjang hidup kami juga di Indonesia, bekerja, menikah, berkeluarga, punya anak di Indonesia,” tuturnya.
Penulis: Ninik Yuniati


